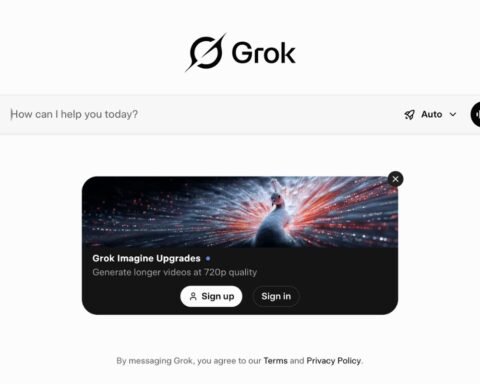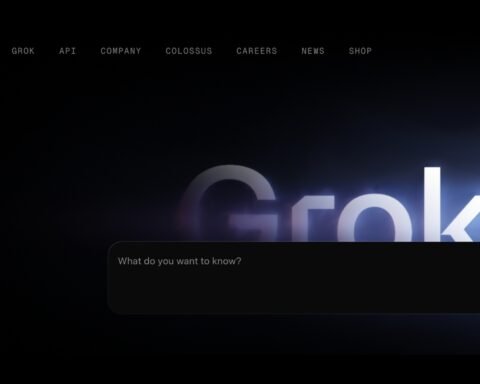Di era digital yang segalanya berjalan begitu cepat, arah kehidupan kita tak lagi hanya ditentukan oleh prinsip pribadi atau nasihat orang tua. Tanpa disadari, banyak dari kita yang kini “menyetir” kehidupan berdasarkan algoritma. Media sosial, khususnya Tiktok, telah bertransformasi dari sekadar platform hiburan, kini sudah menjadi penentu gaya hidup.
Setiap hari kita melihat video yang memberi gambaran tentang bagaimana hidup yang benar menurut media sosial, contohnya cara berpakaian agar terlihat keren dan kekinian, gambaran sukses yang selalu dikaitkan dengan usia muda, penghasilan besar, kehidupan mewah hingga standar dalam memilih pasangan hidup, meski kenyataannya tidak semua orang punya proses yang sama.
Ilusi dalam Durasi 60 Detik
Dalam potongan video berdurasi 15 hingga 60 detik, hidup tampak begitu mudah, murah, dan indah. Kita disuguhi oleh narasi visual yang sempurna: wajah yang selalu terlihat rapi dan segar meski baru bangun tidur, rutinitas bekerja sambil membuka laptop di kafe-kafe mewah, hingga potret kebahagiaan bersama pasangan yang ditampilkan dengan makan malam berdua di restoran ternama, walau faktanya harus menahan hitung-hitungan pengeluaran.
Namun, kita sering lupa bahwa apa yang tersaji di layar adalah produk dari hasil editing yang ketat. Dibalik pencahayaannya yang sempurna dan sudut pengambilan gambar yang presisi, tak jarang ada realitas yang sengaja dipotong. Lelah, cemas, tumpukan tagihan, dan konflik batin tidak pernah masuk dalam frame editing. Dampaknya? Otak kita perlahan tertipu oleh ilusi kolektif bahwa hidup “seharusnya” seperti itu.
Jebakan Perbandingan dan Standar Tak Realistis
Fenomena ini memicu munculnya perasaan tidak puas yang terus menumpuk dan berlarut-larut. Kita mulai mempertanyakan pencapaian diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa:
“Kenapa hidupku begini-begini saja?”
“Kenapa gaji ku masih segini-gini saja?”
Padahal, standar perbandingan yang kita gunakan adalah sesuatu yang tidak nyata. Membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh lika-liku dengan “potongan terbaik” hidup orang lain adalah resep instan menuju rasa rendah diri (insecure). Memaksakan gaya hidup demi validasi digital bukan hanya masalah konsumerisme, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan batin.
Harga Mahal di Balik Sebuah Konten
Lebih jauh lagi, tekanan untuk terlihat tidak kalah dari tren membuat sebagian orang memaksakan diri. Ada yang membeli barang mahal dengan cicilan panjang yang memberatkan, ada pula yang rela berutang hanya untuk menginap semalam di tempat wisata demi konten media sosial.
Semua itu dilakukan bukan untuk kebutuhan, melainkan agar terlihat “sejajar” di layar ponsel. Kebahagiaan yang dirasakan pun tidak bertahan lama, karena hanya bergantung pada jumlah tanda suka dan komentar, yang biasanya hilang begitu unggahan tenggelam oleh konten lain.
Menemukan Kembali Makna “Cukup”
Tiktok pada dasarnya hanyalah alat. Sama seperti alat lainnya, dampaknya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Karena itu, kita perlu lebih pintar dan bijak memilih tontonan. Apakah video yang kita lihat benar-benar memberi semangat untuk maju, atau justru membuat hati tidak tenang dan merasa kurang terus-menerus.
Hidup tidak harus selalu terlihat indah di layar ponsel untuk bisa berarti. Kebahagiaan yang sebenarnya sering lahir dari hal-hal sederhana yang tidak bisa direkam kamera: hati yang tenang, rasa syukur dengan apa yang telah dimiliki, serta kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan keadaan dan kemampuan diri sendiri.
Kesimpulan
Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak jumlah penonton yang kita dapatkan, melainkan seberapa sadar kita menjalani hari. Hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri di dunia nyata, bukan menjadi salinan sempurna di dunia maya.